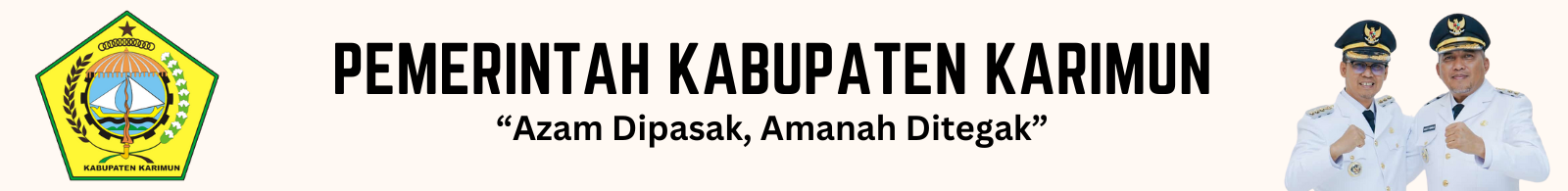(Diolah dari berbagai sumber)
Oleh: Atanasius Dula, S.A.P
Akhir-akhir ini literasi menjadi tema sentral nan seksi dalam berbagai diskusi, seminar hingga pemberitaan media massa. Di kolom opini media tanah air juga acapkali menampilkan pendapat dan diskursus perihal literasi.
Menurut hemat penulis, literasi tidak berdiri hanya sebagai tema tunggal, tetapi bertali-hubung dan tidak terpisahkan dengan tema-tema lain seperti pendidikan, politik, sejarah dan kebudayaan hingga tema-tema strategis semisal human intrrest dan berbagai masalah sosial-kemasyarakatan, tak ketinggalan digitalisasi media yang sedang dilacur HOAX.
Sebagaimana Emile Durkheim yang memandang masyarakat dan fakta sosial, literasi pun dapat dipandang dan kemudian dipahami dalam kerangka sistem sosial, bercakupan luas dan erat bertali dengan tema dan isu-isu lain.
Artinya, literasi (wacana hingga praktik) berhubungan dan bersinggungan langsung dengan hal-hal atau bagian-bagian lain dalam paradigma dan fungsionalisasi struktural tertentu yang beroperasi sebagai sebuah sistem sosial.
Di atas fondamen yang demikian, penulis berupaya untuk menempatkan tema literasi Digital (Upaya Menangkal HOAX) di antara tema-tema yang lain (khususnya pendidikan dan masalah sosial kemasyarakatan) serta konsekuensi yang (mungkin) terjadi dalam hidup kesosialan para pegiat literasi.
Dalam hal ini penulis ingin menegaskan bahwa literasi tidak hanya soal melek huruf-angka, tidak sebatas baca dan tulis. Tidak hanya soal teks dan membaca sebanyak mungkin buku, tidak juga hanya soal bagiamana menulis secara literer. Tidak hanya hanya soal itu, tetapi bagaimana literasi dilihat sebagai sebuah aktivitas intelektual dan kerja otak serta konsekuensi sosial yang terjadi dalam menggunakan media digital, ditengah Masyarakat mondial.
Realitas digital
Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinteraksi agar kehidupan di bumi lebih harmonis dihuni karena orang bebas bicara dan bertukar pikiran dan gagasan ternyata hanya ilusi.
Sejarah membuktikan sebaliknya. Sejak ditemukan mesin cetak yang mempermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, melainkan pidato dan berita beracun bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan keyakianan membahana pula.
Ujaran kebencian dan provokasi yang sekarang disebut hoaks merupakan musuh yang tengah mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini. Faktor penyebab yang paling pertama adalah kehadiran media internet yang semakin masif kepada publik. Internet sejatinya telah menciptakan masyarakat baru yang disebut dengan masyarakat jejaring.
Masyarakat jejaring adalah masyarakat dalam abad informasi di mana fungsi dan peranan semakin banyak ditata dan dikelola di sekitar jejaringan digital berbasis internet (bdk. Castells, 2000:500; Tumenggung 2005: 24). Masyarakat ini memiliki gaya hidup yang virtual yang terbentuk dari efek fisik media serta sistem kerja saraf selalu mengikuti alur media.
Hal ini membenarkan apa yang telah ditandaskan oleh Marshall McLuhan dalam Understanding Media sebagaimana yang dikutip oleh P. Agus Alfons Duka, SVD dalam buku Komunikasi Pastoral Era Digital; bahwa dalam sebuah komunikasi dan interaksi, bukannya pesan yang mempengaruhi pembentukan makna (meaning) dan persepsi manusia, melainkan media.
Media menurutnya dapat mempengaruhi keadaan bawah sadar manusia, sebab ada unsur-unsur tertentu dalam media yang menggiring manusia untuk segera mengambil sikap tertentu sebelum memahami sepenuhnya konten atau muatan yang ditransfer melaluinya. Oleh karena itu media menjadi domain berkecimpungnya individu dalam berbagai kegiatan dan aktivitas virtual melalui identitas siber atau diri virtual.
Identitas demikian dapat dikenal antara lain melalui tulisan pada dinding (wall):Facebook, status di BBM, Twitter, aplikasi WhatsApp, lewat kalimat, gambar, simbol, foto, karakter dan sebagainya. Acapkali tampilan virtual itu nampak dalam curahan hati dan sharing diri kepada publik maya. Aplikasi-aplikasi yang muncul dapat menjadi sarana penampilan diri yang bersifat hic et nunc.
Pengungkapan diri yang virtual tersebut lambat laun bermetamorfosis menjadi sumber ujaran kebencian, fitnah, hasutan dan pencitaraan yang berujung pada xenofobia. Nilai kebenaran tidak lagi menjadi tolok ukur bagi laku dan berterimanya sebuah pesan atau informasi.
Melainkan direkayasa yang berujung pada kejahatan siber serta kejahatan-kejahatan bermotif radikal seperti terorisme dan sebagainya yang tersebar melalui media sosial.
Fenomena Homofilis
Selain faktor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental yakni naluri manusia yang bersifat “homofili”. Fenomena homofilis adalah gejala kecenderungan naluri manusia mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide, dan karakter yang sama.
Relasi yang homofilis semakin mudah kalau didasarkan atas sentimen primordial dan karakter yang sama. Ibaratkan burung yang akan bergerombol dengan jenis burung yang sama.
Pola relasi yang demikian telah merambah dalam media sosial melalui pembentukan kelompok berdasarkan ras, suku, agama, dan golongan yang sama. Kelompok demikian kerap mengumbar informasi atau pesan yang sarat akan pemfitnahan dan kebencian terhadap kelompok-kelompok lain yang dianggap berbeda pandangan dan keyakinan. Dengan demikian terciptalah situasi yang diwarnai dengan pertikaian dan permusuhan bukan hanya dalam media maupun di dunia nyata.
Hingga jelang laga panas kompetensi politik baik Pilkada serentak 2018 maupun Pilpres tahun 2019 yang silam, hoaks semakin gencar merambat meruntuhkan iman politik politisi yang sering rentan terhadap belaian nikmat kuasa. Nilai moral politik ditukar asal dibayar sesuai hasil tawar-menawar pendapat yang menyesatkan serta gaya politik transaksional yang tak terkontrol karena nafsu kuasa yang tak bernalar dan kedap terhadap ajar.
Literasi Digital
Hoaks sebagaimana yang diwacanakan tersebut merupakan musuh negara yang harus segera dilawan. Adapun upaya perlanan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yakni: membentuk Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoaks. Komunitas ini mendeklarasikan gerakan menolak segala bentuk hoaks, seraya mengupayakan di setiap daerah agar membangun sebuah narasi balik melawan hoaks.
Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoaks telah mengembangkan aplikasi telepon seluler bernama “Turn Back Hoax”. Aplikasi ini berisi aduan dan konfirmasi tentang informasi yang diduga berita bohong.
Upaya-upaya ini telah dilaksanakan tetapi masih belum sepenuhnya berhasil. Buktinya bahwa hingga saat ini hoaks masih tak dapat dihentikan dan terbukti masih terdapat kelompok-kelompok yang masih aktif membagi dan menyebarkan konten hoaks seperti kelompok Saracen yang telah memiliki 800.000 pengikut di media sosial. Kelompok ini telah menjual dan menawarkan berita bohong demi meraup keuntungan yang besar.
Oleh karena itu tidak terlepas dari upaya-upaya yang tengah dijalankan tersebut, penulis lebih menawarkan sebuah solusi kritis yaitu memperkuat literasi digital.
Menurut McLaughlin dan De Voohd (2004) sebagaimana yang dikutip oleh Rahma Sugihartati dalam opini berjudul “Komodifikasi Hoaks” (Kompas 29/8), menyatakan literasi digital adalah kemampuan di mana pembaca sebagai partisipan aktif dalam pembacaan dan menjadikan praktik tersebut bergerak melampaui kepasifan menuju penerimaan pesan teks dengan disertai pertanyaan, pengujian atau mengaitkan dengan suatu kekuasaan yang hadir di antara pembaca dan penulis.
Tujuan utama dari literasi digital untuk meningkatkan kemampuan publik dalam memilah informasi yang benar dan tidak benar. Publik dapat mengevaluasi secara kritis dari berbagai perspektif setiap informasi yang ada.
Jacques Derrida salah satu filsuf kenamaan era post-struturalis menawarkan dekonstruksi teks sebagai upaya menyingkap makna-makna yang dipinggirkan, diabaikan atau disembunyikan dalam teks.
Salah satu tujuan dekonstruksi yaitu: menawarkan cara untuk mengidentifikasi kontradiksi dalam politik teks sehingga membantu untuk memperoleh kesadaran lebih tinggi akan adanya bentuk-bentuk inkonsistensi dalam teks. Karena itu, literasi digital seyogianya membuka ilham publik untuk selalu mendekonstruksi setiap informasi yang beredar di media sosial.
Karena itu, tugas pemerintah sekarang melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah melakukan lebih banyak sosialisasi literasi digital kepada masyarakat. Mendidik masyarakat sejak dini untuk selalu bersikap skeptis dan kritis pada informasi bohong niscaya akan jauh lebih bermanfaat daripada semata hanya menekankan kasus penindakan hukumnya.
Karena jika masyarakat kita apatis terhadap literasi digital , maka bukan tidak
mungkin masyarakat akan mudah mengonsumsi hoax. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi penyebar hoax aktif.
(Artikel ini pernah dimuat di media BaPuSe)